Di luar platform tempur, penguatan radar (dengan penambahan unit baru), kerja sama riset hanud dengan lembaga riset nasional, dan kehadiran A400M untuk angkut berat serta resiliensi logistik menunjukkan bahwa kebutuhan khas negara kepulauan mulai terasa direspon lebih serius.
Oleh: Chappy Hakim, Pusat Studi Air Power Indonesia
BERBICARA tentang kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya di matra udara, pilihan alutsista sesungguhnya bukan soal membeli “barang keren”, melainkan hasil tarik-menarik yang rumit antara doktrin, ancaman, politik, ekonomi, kedaulatan, dan kapasitas nasional. Idealnya, setiap keputusan pengadaan selalu diawali satu pertanyaan sederhana namun fundamental yaitu, “apakah alat ini benar-benar mendekatkan kita pada tujuan pertahanan dan kedaulatan, atau justru hanya menambah beban tanpa nilai strategis?”
Dari sudut pandang itu, alutsista udara harus selaras dengan doktrin dan spektrum ancaman yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas.
Kebutuhan akan control of the air dan air denial menuntut prioritas pada radar yang memadai, pesawat tempur yang relevan dengan ancaman kawasan, pesawat intai maritim, rudal hanud, serta sistem komando-kendali (C2) yang mampu mengintegrasikan semuanya.
Di saat yang sama, pilihan alutsista tidak boleh menjadikan Indonesia tersandera embargo dan ketergantungan logistik selama puluhan tahun. Artinya, aspek kedaulatan dan kemandirian mulai dari suku cadang, MRO, hingga penguasaan teknologi kritis, harus diperhitungkan sejak awal, bukan sekadar tambahan manis dalam proposal pengadaan.
Di sisi lain, setiap platform baru membawa implikasi life cycle cost yang besar. Bukan hanya harga beli, tetapi terutama tentang biaya pemeliharaan, upgrade, pelatihan, amunisi, hingga pengelolaan mission data sepanjang masa pakainya. Karena itu, peluang untuk memperkuat industri dalam negeri melalui offset, local content, dan transfer teknologi mesti dikejar secara realistis, tanpa terjebak pada “hadiah politik” jangka pendek atau kebanggaan seremonial belaka.
Pilihan alutsista juga selalu mengirim sinyal geopolitik tentang dengan siapa Indonesia lebih dekat dan interoperable. Komposisinya harus hati-hati, agar di satu sisi membuka ruang kerja sama, tetapi di sisi lain tidak membuat sistem menjadi terlalu rumit dan sulit dipelihara. Pada akhirnya, secanggih apa pun alutsista akan sia-sia apabila tidak serasi dengan kualitas SDM, kultur satuan, dan struktur komando yang mengoperasikannya.
Jika ditinjau secara garis besar, arah pilihan alutsista udara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya bergerak ke jalur yang lebih baik, meskipun masih jauh dari kata rapi dan konsisten. Pengadaan 42 Rafale sebagai tulang punggung tempur multirole, rencana F-15EX untuk superioritas udara jarak jauh, tambahan T-50i untuk training sekaligus light combat, serta keterlibatan kembali dalam program KF-21 menandakan adanya kesadaran bahwa Indonesia harus “naik kelas” di tengah kompetisi kawasan yang semakin keras.
Di luar platform tempur, penguatan radar (dengan penambahan unit baru), kerja sama riset hanud dengan lembaga riset nasional, dan kehadiran A400M untuk angkut berat serta resiliensi logistik menunjukkan bahwa kebutuhan khas negara kepulauan mulai terasa direspon lebih serius.
Namun di tengah tren positif itu, muncul juga langkah yang menyimpan konsekuensi geopolitik dan teknis yang tidak kecil, misalnya wacana masuknya J-10C dari Tiongkok. Jika realisasi pengadaannya terjadi secara penuh, platform ini memang menambah kuantitas serta opsi taktis, tetapi sekaligus mengirim sinyal geopolitik baru di tengah posisi Indonesia yang ingin tetap bebas-aktif.
Dari sudut pandang strategi jangka panjang, paket alutsista seperti ini menyisakan “pekerjaan ekstra” berujud campuran terlalu banyak tipe pesawat antara lain F-16, Su-27/30, Rafale, J-10C, kemungkinan F-15EX, dan KF-21 di masa depan berisiko membuat sistem logistik, pemeliharaan, pelatihan, dan manajemen mission data menjadi sangat kompleks dan mahal. Pengalaman sebelumnya menunjukkan, dengan campuran demikian, jumlah pesawat modern yang benar-benar combat ready setiap hari cenderung menjadi terbatas.
Masalah yang sama juga muncul ketika menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor alutsista udara. Setiap kali Indonesia membeli pesawat, helikopter, radar, atau rudal dari luar negeri, sesungguhnya kita sekaligus mengimpor ketergantungan jangka panjang terhadap suku cadang, amunisi, software, dan paket pemeliharaan yang sewaktu-waktu bisa saja terkena embargo, pembatasan, atau permainan harga.
Dalam jangka pendek, impor memang tidak terhindarkan, karena lompatan teknologi tidak mungkin dikejar sendiri secara instan. Namun tanpa roadmap serius untuk local content, MRO yang kuat di dalam negeri, penguasaan teknologi kritis, serta keberanian menyederhanakan tipe alutsista agar lebih ekonomis untuk dipelihara, Indonesia akan terus berada di posisi rawan yaitu punya pesawat canggih di atas kertas, tetapi tidak sepenuhnya leluasa dalam mengoperasikan dan mengembangkannya.
Jika dikaitkan dengan target Minimum Essential Force (MEF), gambaran besar yang tampak adalah bahwa kemajuan memang ada, tetapi pencapaiannya masih jauh dari tuntas. Beberapa elemen memang menunjukkan progres seperti modernisasi sebagian pesawat tempur, perbaikan radar, pengadaan A400M, penguatan satuan tertentu di matra laut dan darat, namun sebagai sebuah postur terpadu tiga matra yang siap menghadapi skenario konflik bereskalasi, MEF belum benar-benar tercapai baik dari sisi kuantitas maupun kesiapan operasional harian.
Hambatan terbesar bersifat struktural seperti anggaran pertahanan yang relatif kecil dibanding luas wilayah dan kompleksitas ancaman, pola belanja yang sering reaktif dan terfragmentasi, birokrasi pengadaan yang rumit, serta ketidakselarasan antara doktrin, rencana kekuatan jangka panjang, dan kapasitas industri pertahanan nasional. Akibatnya, MEF lebih sering menjadi “target di atas kertas” dibanding panduan operasional untuk membentuk kekuatan yang terukur, terpelihara, dan siap tempur.
Dari sisi komposisi kemampuan, jenis alutsista udara Indonesia sebenarnya sudah bergerak mendekati kebutuhan realistik dan ancaman kawasan yang terdiri dari multirole fighter yang lebih modern, pesawat angkut berat, dan radar yang lebih mutakhir.
Tetapi komposisi itu sendiri belum sepenuhnya ideal. Sistem hanud berlapis, pesawat intai maritim dan AEW&C, UAV/ISR strategis, serta jumlah pesawat tempur yang combat ready per hari masih tertinggal dari kebutuhan untuk menjamin control of the air secara konsisten di seluruh wilayah NKRI.
Di tengah kesenjangan teknologi dibanding negara-negara Asia lain, posisi Indonesia secara jujur masih lebih tepat disebut catching up ketimbang leading. Indonesia belum memiliki keunggulan teknologi yang menonjol dalam modernisasi alutsista udara.
Keunggulan kita justru terletak pada pengalaman operasi di wilayah kepulauan yang ekstrem luas, tradisi profesionalisme penerbang dan ground crew, serta posisi geopolitik non-blok yang memberi ruang untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Potensi ini hanya akan maksimal apabila didukung pendanaan yang konsisten, penyederhanaan tipe alutsista agar sistem lebih efisien, dan penguatan industri dirgantara nasional sebagai tulang punggung jangka panjang.
Dari sisi penempatan kekuatan, postur pangkalan udara Indonesia juga belum ideal. Penempatan skadron tempur dan aset utama masih cenderung terlihat sebagai Jawa-sentris, belum cukup forward deployed di titik-titik kunci seperti Natuna, Selat Malaka, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Konsep base dispersal dan alternate airfield yang kuat juga belum benar-benar diterapkan secara sistematis. Konsekuensinya, jangkauan respons cepat sebenarnya ada, tetapi tidak optimal untuk skenario krisis multi-arah dan konflik bereskalasi di seluruh wilayah NKRI.
Kebijakan pengembangan pesawat tempur, pangkalan, dan alutsista AU lainnya memang bergerak ke arah yang lebih maju, termasuk mulai memikirkan pangkalan di wilayah timur dan garis depan. Namun semua itu belum terajut utuh sebagai satu desain besar yang menyatukan pesawat, pangkalan, hanud, C2, logistik, dan industri pendukung dalam satu grand design pertahanan udara yang terpadu Kodalnya.
Jika seluruh rencana AU dan Kementerian Pertahanan benar-benar terealisasi, dan yang lebih penting lagi didukung oleh sustainment, MRO yang kuat, SDM yang mumpuni, serta jaringan hanud C2 yang terbangun secara konsisten, posisi Indonesia berpotensi naik menjadi kekuatan udara papan tengah-atas di Asia dan salah satu yang terkuat di Asia Tenggara.
Kapasitas control of the air di sekitar choke points utama, Selat Malaka, Natuna, Sulawesi,Maluku, Papua bisa menjadi cukup kredibel untuk menahan, menyulitkan, dan membuat siapa pun berpikir dua kali sebelum melanggar kedaulatan udara NKRI. Kita memang belum akan sekelas Jepang, Tiongkok, atau India dalam hal kuantitas dan teknologi tinggi, tetapi bisa dipandang sebagai middle power dengan daya gentar yang cukup nyata.







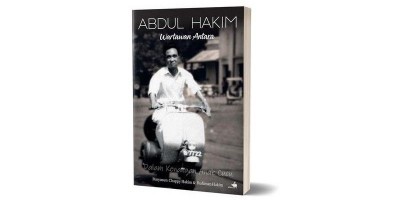









KOMENTAR ANDA