Pesawat dengan kemampuan lepas-landas dan mendarat di landasan pendek, kapasitas menengah, dan sanggup beroperasi di bandara dengan fasilitas terbatas, persis menjawab tantangan geografi Indonesia.
Oleh: Chappy Hakim, Pusat Studi Air Power Indonesia
RAPAT kickoff penyusunan Kebijakan Pengembangan Pesawat Terbang Nasional di Bappenas pada 5 Desember 2025 sesungguhnya bukan sekadar agenda teknis rutin. Di balik forum yang tampak formal itu, tersimpan pertanyaan besar tentang apakah Indonesia sungguh ingin menempatkan langitnya sebagai ruang strategis yang diatur secara sadar, terencana, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang, atau tetap membiarkan kedirgantaraan berjalan dengan pola tambal sulam, sektoral, dan tergantung dinamika pasar semata?
Penguatan industri pesawat terbang nasional tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan pabrik pesawat dan insinyur belaka. Ia melekat langsung pada tiga dimensi penting: konektivitas dan perhubungan udara antarkawasan di seluruh pelosok negeri, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik hingga daerah yang tak tersentuh moda transportasi lain, serta penguatan kedaulatan negara di udara sebagai bagian dari sumber daya strategis nasional.
Karena itu, forum yang digagas Bappenas ini patut dibaca sebagai kesempatan emas untuk menata ulang cara pandang negara terhadap udara Indonesia.
Suasana rapat memperlihatkan satu hal yang menggembirakan: dukungan penuh terhadap pengembangan industri pesawat terbang nasional datang dari hampir semua unsur yang hadir. Pemerintah, pelaku industri, operator, hingga komunitas kedirgantaraan berbagi kesadaran yang sama bahwa Indonesia sudah memiliki modal pengetahuan, pengalaman, dan terlebih lagi kebutuhan pasar domestik yang sangat besar untuk menopang keberlanjutan industri ini.
Terutama di segmen pesawat perintis dan menengah, negeri kepulauan dengan ribuan pulau dan kontur geografi yang ekstrem ini sesungguhnya adalah “laboratorium alam” yang ideal bagi pesawat-pesawat buatan sendiri.
Namun optimisme itu bersisian dengan keprihatinan yang tidak kalah besar. Hampir semua pembicara menyoroti betapa sulitnya berkoordinasi dalam urusan kedirgantaraan nasional. Pengelolaan isu-isu penerbangan – termasuk pengembangan pesawat terbang – belum terintegrasi di tingkat pengambilan keputusan strategis lintas kementerian dan lembaga.
Kebijakan sektoral berjalan sendiri-sendiri, keputusan tentang industri pesawat, perhubungan udara, dan pertahanan udara tidak selalu saling menguatkan, sementara peluang sinergi antara kebutuhan pertahanan, jaringan perhubungan, dan program pembangunan wilayah justru sering terbuang percuma.
Di tengah kondisi seperti itulah mengemuka kembali gagasan yang sebetulnya bukan barang baru: perlunya sebuah Dewan Penerbangan di tingkat nasional. Sebuah wadah yang menjadi rumah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan kedirgantaraan, yang bukan hanya bertugas menyusun arah kebijakan secara terpadu, tetapi juga menjembatani kepentingan sektor pertahanan, perhubungan, industri, dan pembangunan wilayah.
Dewan semacam ini hanya akan efektif bila ditempatkan pada level strategis, sehingga mampu menyatukan suara lintas kementerian dan lembaga, bukan sekadar menjadi forum koordinasi seremonial tanpa daya putus.
Dalam diskusi Bappenas itu, menguat pula kesadaran tentang betapa krusialnya pesawat sekelas CN-235 dan N219 bagi Indonesia. Pesawat dengan kemampuan lepas-landas dan mendarat di landasan pendek, kapasitas menengah, dan sanggup beroperasi di bandara dengan fasilitas terbatas, persis menjawab tantangan geografi Indonesia. Dari rute perintis di wilayah pegunungan Papua, pulau-pulau kecil di Maluku dan Nusa Tenggara, sampai daerah tertinggal yang sulit dijangkau transportasi darat dan laut, pesawat-pesawat inilah yang dapat menjadi urat nadi konektivitas.
Nilainya bukan semata komersial. Kehadiran pesawat tersebut adalah wujud kehadiran negara: menghubungkan desa terpencil dengan pusat pelayanan kesehatan, mengantarkan guru, dokter, obat-obatan, bahan pangan, dan simbol paling nyata bahwa warga di tepian republik tidak ditinggalkan.
Dari sini, satu pelajaran penting muncul dengan sangat jelas: perhubungan udara nasional tidak mungkin diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan maskapai swasta. Banyak negara dengan wilayah relatif kecil, populasi terkonsentrasi, dan infrastruktur yang merata mungkin dapat mengandalkan model bisnis penerbangan yang sepenuhnya berbasis keuntungan.
Indonesia bukan negara seperti itu. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, dengan jutaan warga yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan, dan pulau-pulau kecil, orientasi tunggal pada profit justru berisiko menyingkirkan mereka yang paling membutuhkan kehadiran negara.
Sejarah telah memberikan buktinya. Dalam berbagai momen penting seperti Trikora, Dwikora, operasi di Timor Timur, hingga penanganan bencana besar seperti tsunami Aceh, maskapai milik negara selalu menjadi salah satu tulang punggung utama mobilisasi personel, logistik, dan bantuan kemanusiaan. Pesawat-pesawat inilah yang terbang ketika banyak pihak lain berhitung ulang soal risiko dan keuntungan.
Dalam situasi krisis, negara tidak bisa sekadar berharap pada kebaikan hati pasar. Ada mandat konstitusional yang harus dipenuhi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Karena itu, dalam forum Bappenas mengemuka gagasan bahwa negara setidaknya perlu memastikan keberadaan beberapa jenis maskapai milik negara dengan fungsi yang jelas.
Pertama, flag carrier yang menjaga kehadiran Indonesia di jaringan penerbangan internasional dan nasional utama, sekaligus menjadi simbol kedaulatan dan representasi negara di mata dunia, termasuk dalam pelayanan haji dan umrah.
Kedua, maskapai perintis yang fokus melayani daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan mandat utama pelayanan publik. Ketiga, maskapai charter yang membantu kebutuhan operasi khusus pemerintah, penanganan bencana, misi kemanusiaan, dan kepentingan strategis lainnya, serta dapat memberi fleksibilitas bagi negara dalam merespons dinamika lapangan maupun kebutuhan investasi. Keempat, maskapai kargo yang menggerakkan distribusi logistik nasional, menopang pemerataan pembangunan dan program distribusi bahan pokok, termasuk agenda “satu harga” dari Sabang sampai Merauke.
Fungsi-fungsi seperti kewajiban pelayanan publik, penerbangan ke wilayah sulit, distribusi sembako, dan dukungan administrasi serta logistik pemerintahan jelas tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada operator swasta yang secara alamiah berorientasi laba. Di sinilah maskapai milik negara memegang peran dominan dan strategis.
Mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebagai entitas bisnis yang dinilai semata dari neraca keuntungan dan kerugian, melainkan sebagai instrumen kebijakan negara yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan sekaligus.
Semua kebutuhan di atas bermuara pada satu kesimpulan yang tak terelakkan: Indonesia membutuhkan pesawat buatan sendiri yang dirancang untuk menjawab karakter geografis dan kebutuhan operasional bangsa ini.
CN-235 dan N219, serta varian atau pengembangan di kelas yang sama, harus ditempatkan sebagai platform utama dalam kebijakan pengembangan pesawat nasional. Pesawat-pesawat ini dapat diposisikan sebagai tulang punggung armada rute perintis, kargo di daerah sulit, dan berbagai misi kenegaraan yang menuntut fleksibilitas sekaligus keandalan.







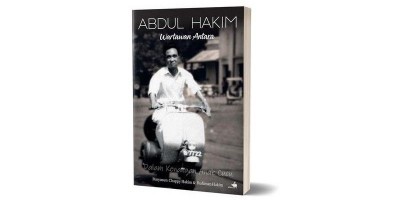









KOMENTAR ANDA